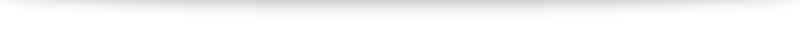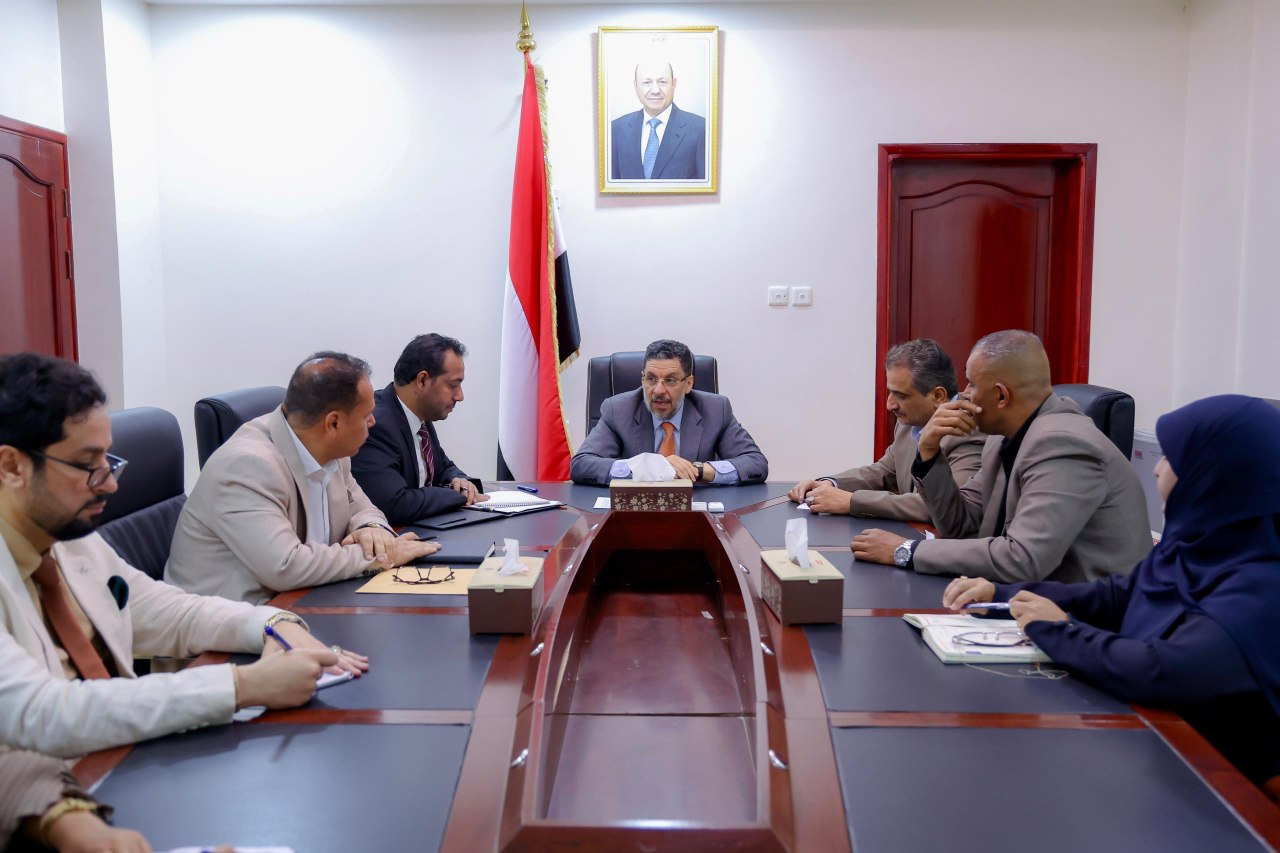Kamp-kamp Palestina di Suriah dan Lebanon telah menempuh perjalanan panjang dari tenda darurat menjadi kawasan urban yang kompleks. Fenomena ini mencerminkan kemampuan pengungsi dalam menyesuaikan diri dengan kondisi jangka panjang. Dari sekadar hunian sementara, kini beberapa kamp memiliki apartemen yang disewakan, toko, bahkan hotel kecil yang melayani pengunjung.
Yarmuk di Damaskus menjadi contoh paling terkenal di Suriah. Didirikan pada 1957–1960-an, kamp ini awalnya menampung pengungsi Palestina yang melarikan diri dari konflik Arab-Israel. Seiring waktu, keluarga Palestina membangun rumah permanen dari beton bertingkat, beberapa di antaranya dijadikan apartemen untuk disewakan.
Transformasi ini bukan hanya sekadar kebutuhan hunian. Warga menyadari bahwa sewa-menyewa apartemen dapat menjadi sumber penghasilan tambahan. Banyak keluarga yang tetap tinggal di lantai bawah rumah mereka, sementara lantai atas disewakan untuk tetangga atau kerabat yang datang dari luar kota.
Selain apartemen, di beberapa kamp di Lebanon, seperti Shatila dan Bourj el-Barajneh, muncul hotel dan penginapan kecil. Fasilitas ini biasanya dikelola oleh warga kamp untuk melayani diaspora Palestina atau kerabat yang datang berkunjung, sekaligus menjadi bagian dari ekonomi internal kamp.
Pasar lokal juga menjadi bagian integral dari urbanisasi kamp. Toko kelontong, roti, warung makanan, bahkan kios pakaian berkembang di sepanjang jalan utama kamp. Aktivitas ini membentuk ekonomi mikro internal yang menopang kehidupan sehari-hari warga.
Fenomena ini menunjukkan kemampuan adaptasi ekonomi yang tinggi. Di tengah keterbatasan hak sipil, terutama di Lebanon, warga kamp Palestina memanfaatkan properti yang mereka miliki untuk menciptakan mata pencaharian. Sewa-menyewa apartemen dan penginapan menjadi salah satu cara bertahan hidup jangka panjang.
Sebelum perang Suriah, Yarmuk tidak hanya menjadi pusat hunian, tetapi juga pusat budaya dan sosial. Masjid, sekolah, dan fasilitas olahraga berdiri berdampingan dengan rumah-rumah bertingkat. Kehidupan sosial yang padat memfasilitasi munculnya aktivitas ekonomi seperti jasa potong rambut, jahit, dan penjualan makanan.
Di Lebanon, kamp seperti Ein el-Hilweh memiliki struktur politik internal. Faksi-faksi Palestina mengawasi kawasan tertentu, dan ini memengaruhi bagaimana aktivitas ekonomi diatur. Meski demikian, praktik sewa-menyewa dan usaha kecil tetap berkembang, membentuk kehidupan urban yang unik.
Urbanisasi ini juga tercermin dalam infrastruktur. Jalan-jalan yang dulunya tanah lapang kini beraspal, listrik dan air tersedia sebagian besar hari, dan jaringan toko-toko kecil memudahkan akses kebutuhan dasar. Semua itu menjadikan kamp lebih menyerupai kota kecil daripada pengungsian sementara.
Fenomena apartemen sewa menandai pergeseran psikologis bagi warga. Mereka tidak lagi melihat kamp sebagai tempat transit, tetapi sebagai rumah permanen, sekaligus peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan.
Hotel kecil dan penginapan juga menjadi simbol urbanisasi. Fasilitas ini memperlihatkan bahwa kamp bisa menyerap pengunjung dari luar, baik diaspora maupun keluarga, sehingga menciptakan interaksi ekonomi dan sosial baru di dalam kamp.
Seiring waktu, generasi muda yang lahir di kamp ini juga berperan dalam ekonomi internal. Banyak anak muda membuka toko, belajar keterampilan perdagangan, atau membantu usaha keluarga, sehingga kamp tetap hidup dan dinamis.
Namun urbanisasi tidak berarti bebas dari keterbatasan. Di Lebanon, warga Palestina masih dibatasi hak kepemilikan tanah dan akses pekerjaan formal. Ini membuat sebagian besar ekonomi kamp tetap informal, bergantung pada modal sendiri dan solidaritas komunitas.
Di Suriah, konflik membawa tantangan baru. Perang menghancurkan beberapa kamp dan mengubah Yarmuk menjadi zona perang. Meski demikian, sebelum konflik, kamp Palestina sudah membentuk jaringan sosial-ekonomi yang kuat.
Kehadiran apartemen sewa dan hotel kecil mencerminkan adaptasi jangka panjang. Pengungsi belajar memanfaatkan aset yang ada untuk menciptakan stabilitas ekonomi, meski status mereka tetap terbatas secara hukum.
Fenomena ini juga menunjukkan perbedaan antara kamp pengungsi darurat dan kamp urbanized. Di Zaatari atau Al-Hol, warga bergantung sepenuhnya pada bantuan internasional, sedangkan di Yarmuk atau Shatila, warga telah mengembangkan ekonomi internal mandiri.
Kamp urbanized juga menjadi pusat budaya Palestina. Masjid, sekolah, toko, dan pasar membentuk komunitas yang mempertahankan identitas nasional meski berada jauh dari tanah air. Ini menjadi kekuatan sosial yang mendukung kegiatan ekonomi lokal.
Solidaritas internal warga kamp memperkuat sistem ekonomi informal. Bantuan antar keluarga, sistem barter, dan jaringan toko kecil menjadi tulang punggung ekonomi yang memungkinkan kamp tetap hidup meski tanpa dukungan negara secara penuh.
Transformasi dari tenda darurat menjadi apartemen, toko, dan hotel kecil juga menandai resiliensi warga Palestina. Mereka mampu menyesuaikan diri dengan kondisi jangka panjang, membangun komunitas, dan tetap mempertahankan identitas nasional.
Kini, kamp Palestina urbanized menjadi contoh unik bagaimana pengungsi bisa mengubah status darurat menjadi permanen, sekaligus membangun ekonomi internal, sosial, dan budaya yang kompleks, meski dengan keterbatasan hukum dan tantangan politik.
Beberapa jenis kamp pengungsi
Jenis pengungsi di Suriah dan Irak cukup beragam karena konflik yang panjang, campur tangan banyak aktor, serta situasi sosial-politik yang berbeda di setiap wilayah. Jika dilihat dari pengelolaan dan bentuknya, secara garis besar bisa dibagi menjadi beberapa kategori:
---
1. Kamp resmi di bawah UNHCR dan lembaga kemanusiaan internasional
Contoh paling dikenal adalah kamp Zaatari di Yordania (untuk pengungsi Suriah), Domiz di Irak (untuk pengungsi Suriah Kurdi), atau Al-Hol di timur laut Suriah.
Di sini, UNHCR (Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi) dan mitra-mitranya mengatur registrasi, distribusi bantuan, layanan kesehatan, pendidikan, serta koordinasi keamanan.
Biasanya kamp ini terorganisir, ada tenda atau bangunan prefabrikasi, jalan, serta fasilitas umum.
---
2. Kamp semi-resmi di bawah otoritas lokal atau milisi
Banyak kamp di Suriah timur laut (dikelola Administrasi Otonomi Kurdi/SDF) atau di Irak yang dikelola pemerintah daerah Kurdistan Irak.
Layanan di sini sering tidak selengkap kamp UNHCR, tapi tetap ada keterlibatan NGO internasional.
Misalnya kamp Hasakah atau Kawrgosk di Erbil.
---
3. Pengungsian mandiri / sporadis di luar kamp
Jutaan pengungsi Suriah dan Irak tinggal di kota-kota besar atau desa-desa tanpa mendaftar ke lembaga resmi.
Mereka menyewa rumah, menumpang di keluarga, atau membangun tempat tinggal darurat.
Ini sering disebut sebagai “urban refugees”. Kondisi mereka sering lebih tidak terlihat, tetapi juga rawan karena minim bantuan resmi.
---
4. Kamp pengungsi internal (IDP camps)
Di Irak: banyak kamp IDP (Internally Displaced Persons) bagi warga yang mengungsi dari Mosul, Fallujah, atau Sinjae.
Di Suriah: IDP camp tersebar di Idlib, Aleppo utara, dan Raqqa, sering berupa tenda darurat di tanah lapang.
Kadang dikelola NGO lokal, kadang hanya swadaya masyarakat.
---
5. Pengungsian berbasis agama/komunitas
Misalnya komunitas Yazidi yang terpusat di kamp Sharya atau di Sinjar, dengan pola bantuan khusus karena identitas mereka.
Demikian juga minoritas Kristen Irak banyak mengungsi ke Ankawa (Erbil) dan membentuk kawasan semi-eksklusif.
---
6. Kamp “tertutup” dengan pengawasan ketat
Salah satu contoh terkenal adalah Kamp Bucca di Irak selatan (di dekat Umm Qasr, Basra). Awalnya dibuat AS untuk menahan ribuan tahanan selama perang Irak pasca 2003.
Meski disebut kamp pengungsi/tahanan, sifatnya lebih mirip penjara militer ketimbang kamp kemanusiaan.
Di Suriah, ada juga kamp Al-Hol yang mirip “semi-penjara”, dengan pengawasan ketat dan mobilitas terbatas.
---
7. Penampungan sementara di sekolah, gedung kosong, atau tenda darurat
Saat gelombang pengungsian besar (misalnya setelah jatuhnya Mosul 2014 atau Aleppo 2016), banyak keluarga tinggal di sekolah, stadion, atau bangunan kosong sebelum dipindahkan ke kamp permanen.
---
Jadi, jika disederhanakan, ada tiga poros besar jenis pengungsian di Suriah dan Irak:
1. Pengungsian resmi dan semi-resmi (dikelola UNHCR, pemerintah, atau otoritas lokal).
2. Pengungsian mandiri/urban refugees (tidak terdaftar, hidup sporadis di kota atau desa).
3. Kamp tertutup/penahanan (seperti Bucca di Irak atau Al-Hol di Suriah) yang lebih menyerupai fasilitas keamanan dibanding pengungsian biasa.
____
Di kamp Al-Hol (timur laut Suriah, dekat perbatasan Irak), meski statusnya sering digambarkan mirip “penjara terbuka”, ternyata ada juga pasar internal dan aktivitas ekonomi yang tumbuh di antara para penghuninya.
Beberapa hal yang tercatat dari laporan lapangan:
Pasar kecil (souq) muncul secara spontan di dalam kamp. Warga menjual bahan makanan, pakaian, roti, bahkan barang-barang kecil lain. Ada kios-kios darurat dari kayu, terpal, atau papan.
Banyak aktivitas itu dijalankan oleh penghuni sendiri. Sebagian modal didapat dari kiriman uang keluarga melalui jaringan informal (hawala) atau bantuan yang ditukar.
Ada pula perdagangan gelap — barang-barang masuk lewat penjaga kamp atau penyelundupan, terutama rokok, obat-obatan, bahkan ponsel.
Jasa informal juga berkembang: menjahit, potong rambut, membuat roti, atau tukang cuci pakaian.
Namun aktivitas ekonomi ini tidak bebas. Semua di bawah pengawasan ketat pasukan Kurdi (SDF). Beberapa zona bahkan dipisahkan, khususnya bagi keluarga asing anggota ISIS yang aksesnya lebih terbatas.
Pendapatan yang didapat sangat minim, tapi bagi penghuni kamp, aktivitas ekonomi kecil-kecilan itu adalah cara bertahan hidup, apalagi karena bantuan resmi sering tidak mencukupi.
Jadi, meski Al-Hol identik dengan kontrol militer dan stigma penjara, di dalamnya tetap muncul ekonomi bayangan khas pengungsian: pasar sederhana, barter, dan usaha kecil yang dijalankan para penghuni untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
---
TENTANG kamp Palestina di Suriah dan Lebanon, yang awalnya memang dimulai sebagai tenda-tenda pengungsian sejak 1948 dan 1967, kini banyak di antaranya sudah berkembang menjadi kota permanen dengan ribuan bangunan beton.
Secara kategori, kamp-kamp seperti ini berada di posisi unik, bukan sepenuhnya “kamp pengungsi darurat” tapi juga bukan kota biasa. Mereka lebih tepat disebut:
1. Kamp permanen / urbanized camps
Awalnya didirikan UNRWA (Badan PBB untuk Pengungsi Palestina) sebagai kamp pengungsian sementara.
Tapi seiring waktu, keluarga Palestina membangun rumah permanen dari beton, membentuk jalan, sekolah, masjid, bahkan pasar.
Contoh: Yarmuk di Damaskus (Suriah), Shatila dan Bourj el-Barajneh di Beirut (Lebanon).
Secara fisik, sudah mirip kota padat, tapi status hukumnya tetap “kamp pengungsi” di bawah UNRWA.
2. Kawasan semi-otonom dengan identitas kuat Palestina
Di Lebanon, kamp-kamp Palestina punya status khusus: tidak sepenuhnya di bawah hukum Lebanon, tapi juga tidak independen.
Misalnya di Ein el-Hilweh (Sidon, Lebanon), ada struktur politik internal sendiri, kadang dipimpin faksi-faksi Palestina (Fatah, Hamas, atau kelompok independen).
Di Suriah sebelum perang, kamp Palestina lebih terintegrasi dengan masyarakat Suriah. Yarmuk bahkan disebut “ibu kota diaspora Palestina”.
3. Kategori perumahan pengungsi permanen
Kalau dibandingkan dengan pengungsian Suriah atau Irak, mereka tidak lagi masuk kategori kamp darurat atau IDP camp, melainkan lebih mirip kota pengungsi permanen.
Jadi, bisa dikatakan mereka termasuk dalam kategori urban refugees settlement: sebuah kamp pengungsi yang telah berubah menjadi kawasan perkotaan dengan struktur sosial, ekonomi, dan budaya yang relatif mandiri.
---
📌 Jadi singkatnya:
Kamp Palestina di Suriah dan Lebanon yang sudah menjadi kota = kategori "kamp permanen/urbanized camp".
Mereka berbeda dengan kamp darurat seperti Zaatari di Yordania atau Al-Hol di Suriah.
Statusnya juga unik: secara hukum tetap disebut “kamp pengungsi” oleh UNRWA, tapi kenyataannya mereka sudah berfungsi seperti kota dengan kehidupan sosial-ekonomi penuh.
---